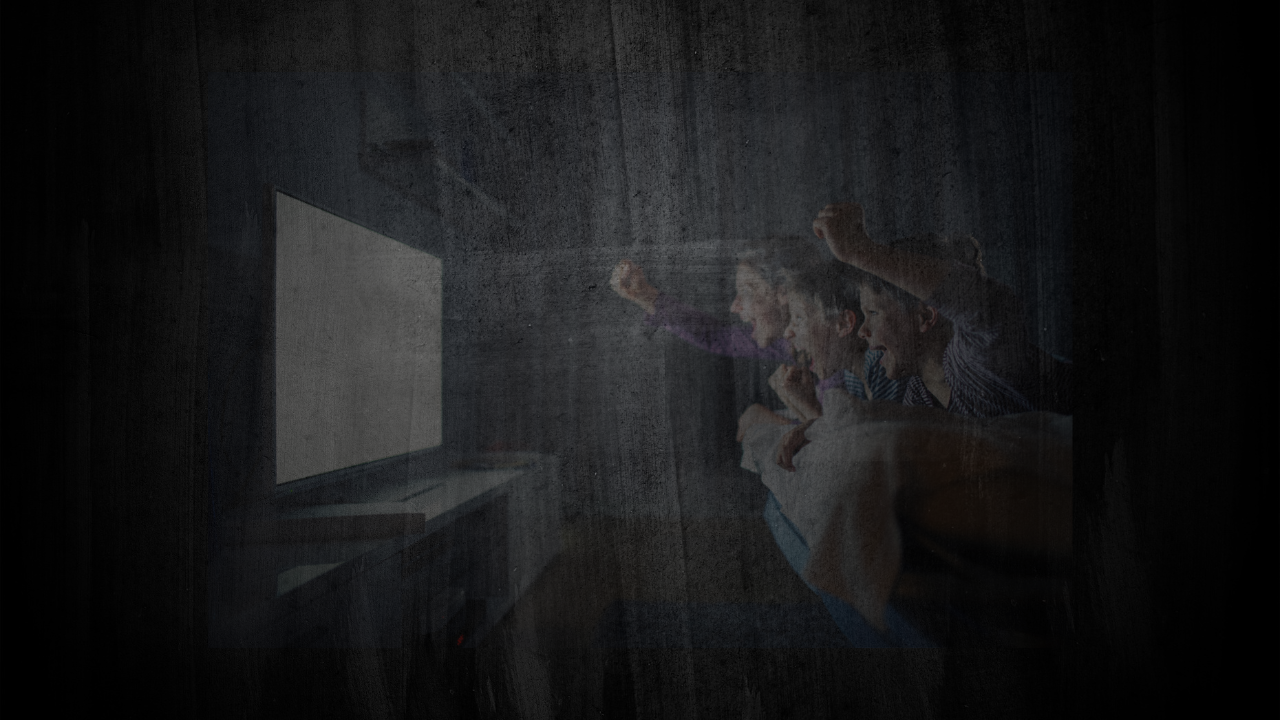Merauke (4/11/2024)- Pagi baru saja mencuat, aroma rawa-rawa Merauke basah oleh embun, ketika Presiden Prabowo Subianto, ditemani para petinggi negara, menginjakkan kakinya di ujung timur Nusantara. Sebuah ironi; di tengah kegemilangan visi swasembada pangan, tanah Papua ini turut menyelipkan cerita tentang keringat, ketakutan, dan lahan-lahan yang memerah oleh protes sunyi masyarakat adat.
Di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, yang membentang sejauh mata memandang, proyek sawah jutaan hektare ini bagai kolosal peradaban baru, sementara keanggunan hutan-hutan asli beringsut, beriring dengan jengkal demi jengkal kehidupan. Tak jauh dari sini, Wanam, Distrik Ilwayab, menjadi panggung utama transformasi raksasa ini, di bawah bayangan ekskavator yang berderak dan naungan militer bersenjata lengkap. Sebuah pemandangan yang bagi masyarakat adat terasa asing, lebih seperti barak perang ketimbang area pertanian.
Namun, alih-alih narasi keberhasilan, suara masyarakat adat Malind perlahan membentuk orkestrasi penolakan yang menggema. Simon Petrus Balagaize, Ketua Forum Masyarakat Adat Malind dan Kondodigun, dengan getir menceritakan bagaimana ritual adat tak lagi sakral sejak hutan di Wogikel dan Wanam mulai tersibak paksa. Dalam ritual dan tangis, tanah kelahiran mereka, tanah yang berpuluh-puluh generasi telah digenggam erat, terasa direnggut. Wajah-wajah mereka kerap berlumur lumpur putih – bukan dalam rangka perayaan, melainkan ekspresi duka dan perlawanan sunyi.
Pada sebuah pertemuan di Dusun Payung Merauke, suara-suara adat dan kata-kata sepakat mengalun untuk menolak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. “Tak ada sosialisasi, tak ada persetujuan. Tanah kami diambil begitu saja,” keluh Balagaize dengan suara yang lebih sering dibungkam oleh kedatangan tamu-tamu tak diundang—intelijen yang kerap mengawasi, seolah-olah kehidupan sehari-hari masyarakat adat adalah ancaman bagi negara.
Sejak PSN mencaplok dua juta hektare wilayah Merauke, bukan hanya tanah yang lenyap. Hubungan antara manusia dan alam, antara budaya dan warisan leluhur, retak tak bisa terobati. Ekspansi perkebunan tebu yang merambat dibekingi oleh kekuatan TNI—menggetarkan masyarakat adat hingga menyulut api protes. Seorang perempuan adat bernama Yasinta Moyuwend, yang berani bersuara menolak PSN, kini dihantui ketakutan tiap kali dua intel datang menyoal keberanian mereka merajut lumpur putih di wajah, sebuah simbolisasi perlawanan.
Ancaman bukan hanya terbatas pada kata-kata. Kisah yang lebih perih datang dari seorang pemuda di Kampung Wanam, yang nyawanya dipertaruhkan ketika lima personel TNI mengancamnya karena berusaha menghalau ekskavator dari area sakral tanah Malind. “Bila Bapak mau tembak saya, silahkan. Ini tanah saya, ini kampung saya,” ucapnya dengan keberanian yang terasa rapuh namun keras seperti besi. Masyarakat adat kini berhadapan bukan hanya dengan perusahaan yang menderu menebas hutan, tapi dengan tembok kokoh berwujud aparat yang menjaga, mengawasi, dan menghantui.
Dampak PSN bagi masyarakat adat tak hanya merenggut hutan dan rawa. Pohon sagu, rusa, kasuari, hingga kuskus, seluruhnya lenyap tanpa jejak. Habitat-habitat yang dulunya dekat kini jadi semakin jauh; batas hidup berubah bersama raung ekskavator. Seorang warga dari Marga Rahol menuturkan bagaimana tanah adatnya kini sekadar cerita dalam bayang-bayang. “Kami yang bertahan hidup dari tanah, kini harus hidup di atas puing-puing kenangan,” ucapnya getir.
Romo Pius Cornelius Manu, seorang pendeta di tanah Merauke, berulang kali merasakan bagaimana intipan mata intel saat diskusi sederhana mereka berubah menjadi teror psikologis yang membekukan. “Kehidupan di sini sudah tidak bebas. Kami bahkan tidak bisa berbisik dalam ketenangan,” ujarnya. Bagi Manu dan masyarakat adat, kehadiran militer di setiap sudut tanah mereka adalah kabut tebal yang membungkam aspirasi.
Kisah Merauke hari ini mungkin adalah sepenggal tragedi yang tak hanya tertulis di atas kertas, tapi juga terukir dalam hati mereka yang kehilangan. Ketika pemerintah mengagungkan swasembada pangan, di tanah Papua ini, masyarakat adat menyadari bahwa janji kesejahteraan adalah utopia yang hanya mampu digenggam dalam mimpi. Harapan seakan menguap bersama asap mesin dan deru alat-alat berat. Bagi masyarakat adat Malind, perjuangan bukan sekadar melawan mesin dan militer, tetapi mempertahankan harga diri dan hak hidup di tanah kelahiran mereka.
Di balik mata yang terus awas mengawasi, di dalam hati yang resah, masyarakat adat Papua menunggu saat tanah ini kembali pada mereka, bukan sebagai ladang sawah, bukan sebagai lokasi proyek, tetapi sebagai rumah – tanah yang mereka jaga dengan segenap jiwa, bukan dengan deru mesin, melainkan dengan doa yang lirih, lirih namun lantang. (CR-7)